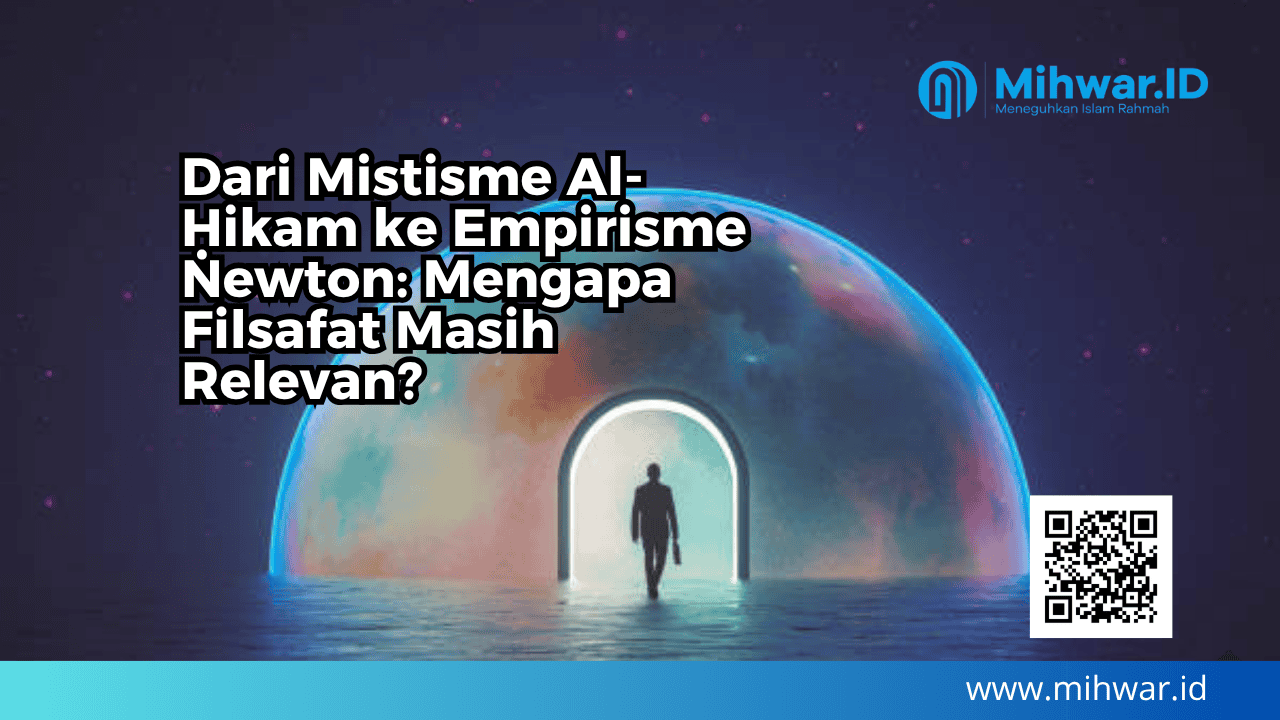Di Barat, Tasawuf dalam Islam kerap diistilahkan dengan mistisme atau ajaran mistik. Beberapa hari belakangan, saya mendapati sebagian orang mempersoalkan penyematan istilah “mistis” terhadap ilmu tasawuf.
Istilah “mistis” di Indonesia sering dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perdukunan atau hal-hal gaib yang bersifat supranatural. Namun, tidak demikian dengan konsep mistisme di Barat—konsepnya jauh lebih umum dan bersifat filosofis.
Sebatas yang saya pahami dari kajian Islamic Studies di Barat—saya hanya mereka-reka berdasarkan pengalaman masa kuliah saat mengikuti mata kuliah Metodologi Studi Islam di UIN Sunan Ampel—ilmu tasawuf di Barat memang dimaknai sebagai Islamic Mysticism. Hanya saja, maknanya masih terbatas dan tidak mencakup seluruh ruang lingkup tasawuf.
Sebagai sedikit klarifikasi: kendati istilah Islamic Mysticism disematkan pada ilmu tasawuf, tidak semua ajaran tasawuf masuk dalam kategori mistisme tersebut. Ada bagian-bagian tertentu dalam tasawuf yang menjadi fokus kajian mereka.
Misalnya, ajaran tasawuf akhlaki—seperti cara makan yang benar, tata cara masuk dan keluar kamar mandi, adab murid terhadap guru, dan sejenisnya—tidak termasuk dalam kategorisasi mistisme dalam kajian Islamic Studies di Barat.
Yang dimaksud dengan Islamic Mysticism lebih merujuk pada ajaran sufisme yang sifatnya filosofis. Misalnya, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Imam Ibn ‘Arabi atau Imam Ibn ‘Atha’illah dalam beberapa maqālah-nya di Al-Ḥikam.
Jika kita membaca maqālah-maqālah Al-Ḥikam, terdapat unsur-unsur filsafat ketuhanan yang menarik untuk diangkat dalam kajian filsafat. Menariknya, sebagian maqālah dalam Al-Ḥikam bahkan bisa ditafsirkan secara liberal. Dengan latar belakang agama apa pun, seseorang tetap dapat mengambil hikmah hidup dari ajaran-ajaran filosofisnya.
Sedikit menceritakan pengalaman pribadi. Dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam, saya mendapatkan IPK A—berkah dari mengangkat salah satu maqālah Al-Ḥikam al-‘Aṭā’iyyah yang saya jelaskan dengan analogi sederhana dalam tugas makalah. Padahal, dalam mata kuliah ini mahasiswa wajib presentasi dalam bahasa Inggris—sementara saya sendiri tidak menguasainya.
Maqālah yang saya angkat adalah maqālah ke-14 dalam kitab Al-Ḥikam. Secara umum, maqālah ini menjelaskan pentingnya melihat suatu objek dengan pandangan filosofis, bukan sekadar pengamatan lahiriah. Imam Ibn ‘Atha’illah menulis:
Al-kaunu kulluhu zulmah, wa innamā anārah ẓuhūru al-Ḥaqqi fīhi. Fa-man ra’ā al-kauna wa lam yushāhid-hu fīhi, faqad a‘wazahu wujūdu al-anwār, wa ḥujibat ‘anhu shumus al-ma‘ārifi bisuḥubi al-āthār
“Segala sesuatu (al-kaun) adalah kegelapan. Hanya cahaya Sang Kebenaran yang meneranginya. Barang siapa memandang alam tetapi tidak menyaksikan-Nya di dalamnya, sungguh ia telah kehilangan cahaya-cahaya Ilahi. Dan matahari-matahari makrifat telah tertutup dari dirinya oleh awan-awan duniawi.”
Membaca maqālah ini, saya jadi teringat Isac Newton yang menemukan teori gravitasi karena melihat buah jatuh dari pohon. Artinya, seorang yang berfilsafat akan menemukan makna dari sekadar apa yang ia amati. Orang yang berfilsafat akan mendalam ketika mengamati dan menjalani suatu pekerjaan.
Tanpa berfilsafat, bagaimana mungkin manusia bisa menghargai emas yang awalnya hanyalah bongkahan kecil di bawah tumpukan tanah? Minyak bumi yang tampak seperti cairan biasa, bisa menjadi bahan bakar penting dalam dunia transportasi. Di sinilah letak pentingnya filsafat dalam kehidupan manusia. Berawal dari menggali hal mistis, sebuah kebenaran dapat terungkap melalui pendekatan filsafat.
Kebenaran dalam keilmuan sains adalah fakta empiris. Sementara kebenaran dalam ilmu sufi adalah mengenal Allah dalam setiap langkah dan gerak.
Misalnya, dari maqālah Al-Ḥikam ini bisa kita pahami bahwa ketika seseorang telah dianugerahi makrifat, maka segala sesuatu di sekitarnya menjadi medan untuk mengenal Allah. Ia tidak lagi melihat tumbuhan sekadar tumbuhan, uang sekadar harta, atau persoalan hidup sebagai tumpukan ujian belaka.
Contoh misalnya; melihat laptop sebagai teknologi canggih. Seorang yang berfilsafat, sebagaimana yang diajarkan Imam Ibn ‘Atha’illah, tidak akan hanya melihat kecanggihannya. Ia akan menggali lebih dalam—bagaimana laptop bisa dibuat oleh manusia, lalu bertanya, mengapa manusia bisa sekreatif dan sepintar itu? Pada akhirnya ia akan menyimpulkan bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan kecerdasan dan ilmu kepada manusia. Puncaknya adalah ketuhanan.
Hal-hal sederhana seperti ini memberi informasi bahwa filsafat memiliki kedudukan penting. Mistisme yang digali melalui filsafat bisa berujung pada penemuan kebenaran hakiki. Mengatakan filsafat tidak penting mungkin saja bisa dibenarkan, jika kita melihat realitas pelajar saat ini yang menjadikan filsafat sekadar bahan obrolan. Mereka belum cukup cakap memahami secara mendalam.
Filsafat tergerus menjadi untaian kata. Mahasiswa Ushuluddin berfilsafat hanya di bibir. Suaranya terdengar filosofis, tapi kosong dari makna. Filsafat bukan hanya untuk dibicarakan, tetapi dipakai sebagai pembangun peradaban—membentuk pemikiran di tengah hedonisme, melahirkan ilmu pengetahuan di tengah kapitalisme. Filsafat adalah Ibu semua Ilmu Pengetahuan.
Tabik.