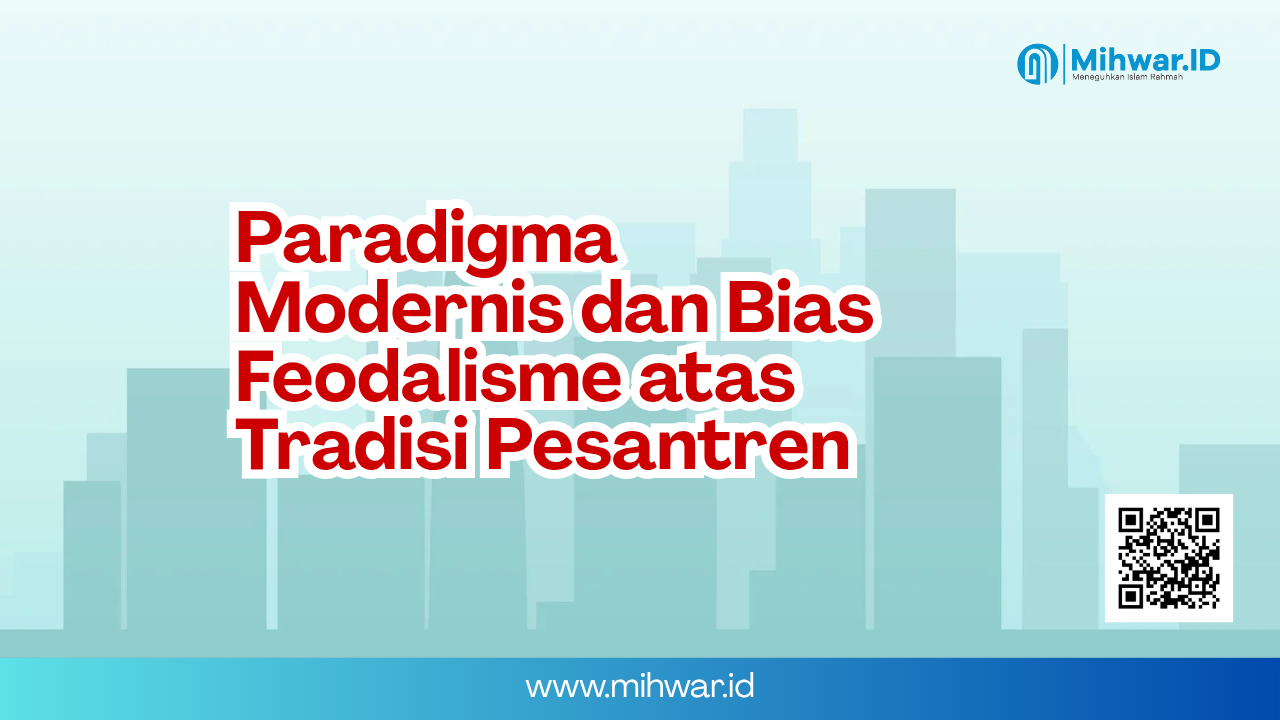Akhir-akhir ini, negara Islam sedang menjadi momok pembicaraan. Latar belakang kegelisahannya adalah karena beberapa abad belakangan, negara yang dihuni mayoritas Muslim dianggap tertinggal. Darinya kemudian muncullah berbagai opini mengapa bangsa-bangsa Muslim tertinggal.
Kegelisahan ini pada dasarnya telah lahir beberapa puluh tahun yang lalu. Di antaranya muncul tokoh-tokoh modernis seperti Muhammad Abduh dan muridnya, Rasyid Ridha, serta beberapa sarjana revisionis Islam seperti Nasr Hamid Abu Zayd, Zaghlul Al-Najjar, Fazlur Rahman, dan beberapa sarjana yang dalam dunia akademik disebut sarjana pembaharu.
Dari kegelisahan-kegelisahan tersebut, lantas kemudian para tokoh modernis terpantik kembali mencari akar ketertinggalan bangsa-bangsa Muslim. Dibukalah sumber-sumber utama Islam, mengkaji kembali Al-Qur’an dan Hadis untuk mengurai persoalan dan solusinya. Tidak hanya pada Al-Qur’an dan Hadis, tetapi juga budaya dan sumber lahirnya budaya yang menjadi tradisi di masyarakat Muslim.
Di Indonesia, sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, gerakan-gerakan mereka memengaruhi para tokoh intelektual lokal. Pada akhirnya lahirlah berbagai pemahaman modern sekular yang mengkritisi tradisi masyarakat Muslim tradisional. Misalnya kritik terhadap ziarah kubur, pengkultusan terhadap tokoh agama, amalan-amalan supranatural dengan mengkritik jimat, dan isu yang sejenis.
Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia tidak luput dari sorotan. Tidak hanya pesantren di Indonesia, tetapi di Mesir, yang terdapat lembaga dengan hampir memiliki visi yang sama seperti pesantren, yaitu Al-Azhar, juga menjadi objek sorotan. Budaya pesantren, kitab-kitab di pesantren, dan gaya komunikasi juga disorot dan dijadikan sebagai sampel untuk menggiring opini bahwa tradisi-tradisi itulah yang menyebabkan bangsa Islam tidak maju.
Feodalisme sebagai Pendekatan Kritik
Bagi kalangan modernis telah disadari bahwa pendekatan-pendekatan keagamaan tidak akan mampu melumpuhkan eksistensi tradisi pesantren di Indonesia. Setiap kritik yang dilontarkan pasti akan selalu gugur dikounter dengan argumentasi para tokoh pesantren, seperti tentang ngalap berkah, ziarah kubur, jimat, tahlilan, dan sejenisnya, sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh salafi dengan semangat pemurnian Islam. Lantas kritik modernitas itu dimunculkan dalam posisi yang lebih sekular dan digandrungi oleh masyarakat modern.
Misalnya kita mengambil contoh penyematan tradisi “feodalisme” di pesantren. Pendekatan istilah ini terhadap pesantren tentu juga telah mereka sadari bahwa yang dimaksud bukan feodal dalam arti pertama kali istilah tersebut muncul dan menjadi objek kritik. Memperpanjang perdebatan tentang istilah ini dengan mendudukkan kedua istilah justru mereduksi suatu hal yang tidak seharusnya.
“Feodalisme” yang disematkan oleh golongan modernis ini dibawa pada paradigma kritik. Maksudnya, istilah ini dikenalkan sebagai upaya bahwa ada unsur-unsur semifeodal dalam pesantren yang perlu dikaji ulang. Seolah-olah kita diajak untuk membuka sejarah, bagaimana pernah terjadi kritik terhadap feodalisme murni dan dihujat habis-habisan oleh masyarakat dunia, khususnya di Barat pada abad pasca-Renaissance.
Motif para kalangan modernis sebenarnya bukan pada tradisi. Mereka ingin menumbuhkan semangat modernisme ala Barat dalam tradisi pesantren sebagai lembaga tradisional. Dari sinilah kesalahan dan perdebatan muncul. Satu golongan berpandangan modernis Barat guna membangkitkan bangsa Muslim, dan satu golongan berpandangan akhlak tradisional sebagai nilai ajaran Islam yang perlu dipertahankan.
Tidak seperti kritik atas feodalisme pada masa lalu, yang disambut baik oleh kalangan bawah yang tertindas sehingga tradisi ini mendapat perlawanan dan dihapus dalam tradisi dunia Barat, penyematan feodalisme pesantren justru disambut baik dengan makna baru.
Lahirlah berbagai pernyataan: “Jika menghormati guru dianggap sebagai budak, lebih baik jadi ‘budak’ seumur hidup.” Dari sinilah akan muncul sebuah pemahaman dan pertanyaan baru: Apakah penghormatan guru dan semangat khidmah di pesantren penyebab kemunduran Islam? Pernyataan inilah yang perlu diuji dan diperdebatkan, sementara istilah “feodalisme” ditangguhkan.
Relasi Hierarkis dalam Kehidupan Pesantren
Para kalangan modernis memberikan kritik terhadap pesantren dengan menyematkan istilah feodalisme yang telah dipahami pada masa awal sebagai tradisi negatif. Sementara itu, tradisi hierarkis sebagai sebuah keniscayaan manusia tidak dipahami penuh. Nilai-nilai hierarkis dalam kehidupan hampir dijumpai di berbagai tempat: karyawan terhadap bos atau atasan, setiap tindakan karyawan perlu patuh pada arahan dan perintah atasan; pejabat pemerintah dengan pejabat yang di atasnya; pemerintah dan rakyat; anak kepada orang tua yang perlu patuh dan berbakti; termasuk seorang murid terhadap guru.
Bentuk hierarkis ini niscaya dalam kehidupan. Bagaimana mungkin semua orang akan setara dalam segala hal? Tidak akan ada pengatur, penunjuk, dan pengawas kehidupan. Egaliter dalam arti kesetaraan bukan berarti menafikan peran atasan dan bawahan dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Nilai egaliter pada dasarnya terletak pada kesadaran akan pentingnya memahami posisi yang niscaya itu. Menjadi atasan tidak boleh sewenang-wenang, demikian pula bawahan menyadari nilai batas menyetarakan diri.
Dari sinilah akhlak lahir. Pada dasarnya, akhlak adalah konsep, bukan tentang membungkukkan badan, jalan ngesot, cium tangan, dan tersenyum. Itu semua adalah ekspresi akhlak dari keniscayaan hierarkis tadi. Sebagai sebuah ekspresi, setiap komunitas memiliki tradisi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, orang-orang pesantren akan berada pada posisi berbeda dalam berekspresi ketika berada dalam komunitas berbeda. Apabila di pesantren membungkukkan badan di hadapan gurunya, bisa saja tidak demikian dalam komunitas lain, kendati dalam struktur hierarkis yang sama.
Sebagai sebuah tradisi, tidak ada pola atau sistem yang mengatur. Semuanya berjalan secara alamiah. Bagaimana orang-orang Barat memanggil dosennya dengan langsung menyebut nama tanpa diawali “bapak”, bagi mereka adalah hal yang wajar. Tetapi pada akhirnya mengakui keilmuan dan tunduk adalah hal yang lain. Apakah mereka lalu kita kritik tidak berakhlak, atau justru kita puja karena semangat egaliter dihadirkan? Kembali pada pemahaman tadi: egaliter dan akhlak adalah konsep, sementara ekspresi adalah gestur dan gimik.
Egaliter adalah nilai universal akhlak, sementara ekspresi adalah tradisi yang tidak disimbolkan hanya oleh standar komunitas tertentu.