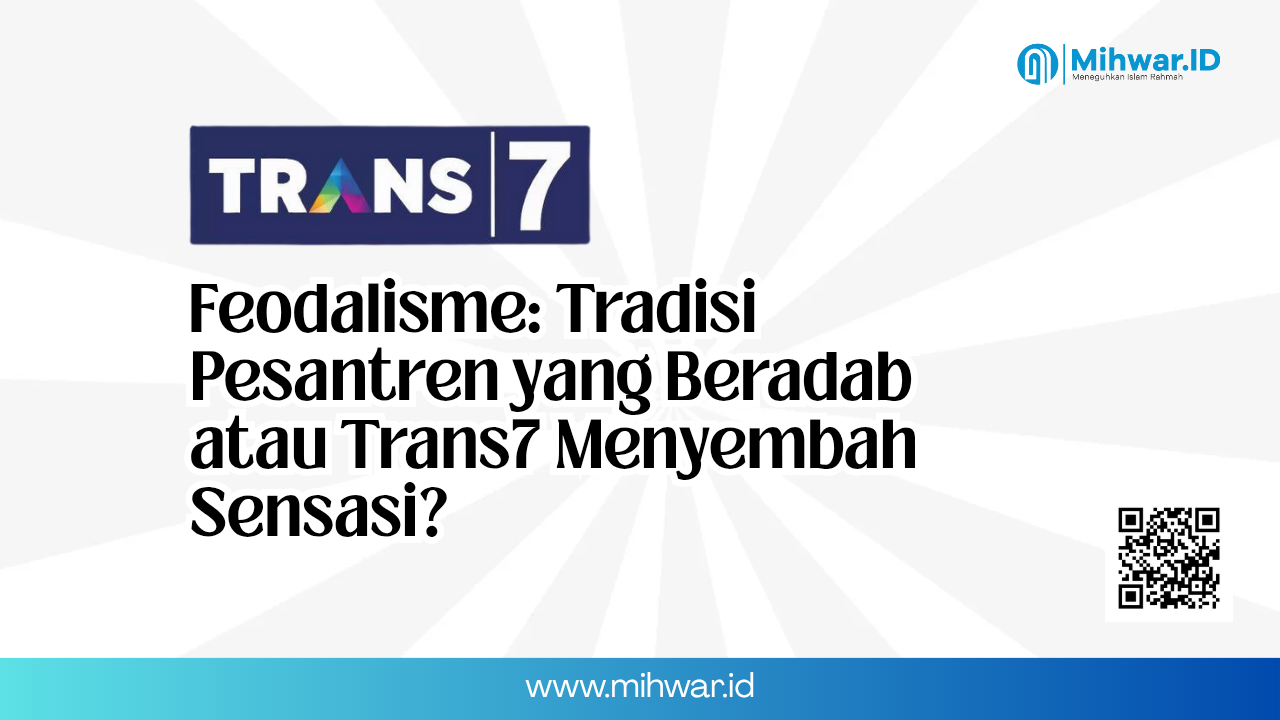Oleh: N.A. Tohirin
Di pesantren, adab selalu lebih tinggi dari ilmu. Kalimat itu sering diulang oleh para kiai dari generasi ke generasi, seolah menjadi mantra moral yang menjaga nyala keikhlasan di tengah perubahan zaman. “Al-adabu fauqal ‘ilm,” kata mereka dengan nada lembut tapi tegas—adab di atas ilmu. Ia bukan sekadar pepatah, melainkan prinsip hidup yang menuntun santri agar tak terjebak pada kesombongan intelektual. Dalam pandangan pesantren, ilmu tanpa adab hanyalah kebodohan yang berwajah pandai. Tetapi kini, nilai luhur itu tiba-tiba dicurigai, bahkan dicap sebagai bentuk feodalisme oleh sebuah tayangan di televisi nasional, Trans7, yang mencoba menggugat relasi antara kiai dan santri sebagai hubungan yang tidak setara, penuh kepatuhan buta, dan berpotensi menumbuhkan otoritarianisme budaya.
Tayangan itu, dengan gaya penyusunan gambar yang dramatis, menampilkan santri yang jongkok dan menunduk mencium tangan kiai, lalu menempatkannya dalam narasi yang menuduh bahwa dunia pesantren masih terbelenggu oleh “budaya tunduk”. Dalam tayangan tersebut, itu adalah bentuk feodalisme baru di dunia pendidikan: ketika murid kehilangan daya kritis dan guru menjadi penguasa yang tak boleh dibantah. Tapi, benarkah demikian? Apakah adab yang diajarkan di pesantren benar-benar sama dengan feodalisme yang menindas manusia?
Dalam tradisi Islam, penghormatan kepada guru adalah bagian dari etika spiritual. Kitab Ta‘lim al-Muta‘allim karya Syekh al-Zarnuji, kitab klasik yang diajarkan hampir di setiap pesantren di Indonesia, menulis dengan jelas, “Man lam yu‘azzim ‘alimahu, lam yantafi‘ bi ‘ilmihi,” barang siapa tidak memuliakan gurunya, maka ia tidak akan mendapat manfaat dari ilmunya. Kalimat itu tidak sedang menciptakan hubungan kekuasaan, melainkan menjelaskan logika spiritual: ilmu adalah cahaya (nur), dan hati yang tidak bersih oleh adab tidak akan mampu menampung cahaya itu. Dalam pandangan Zarnuji, adab bukanlah sistem sosial, tapi kondisi batin yang menentukan keberkahan ilmu.
Namun, media modern seperti Trans7 menafsirkan penghormatan itu melalui kacamata politik kekuasaan. Mereka melihat tunduknya santri pada kiai bukan sebagai laku spiritual, tetapi sebagai simbol ketimpangan. Padahal, yang terjadi di pesantren justru sebaliknya: penghormatan lahir dari cinta, bukan dari takut. Kiai bukan penguasa; ia adalah pengasuh. Santri tidak diperintah untuk patuh, tapi dituntun untuk memahami bahwa ilmu yang sejati hanya tumbuh dari kerendahan hati.
Imam al-Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulumiddin menulis, “Tidak akan sampai seseorang kepada kebenaran kecuali dengan menghormati siapa yang menunjukkan jalan kepadanya.” Dalam pandangan al-Ghazali, penghormatan itu bukan bentuk ketertundukan sosial, melainkan pengakuan bahwa manusia belajar kebenaran melalui perantara—dan perantara itu harus dijaga kehormatannya. Dalam konsep Islam, ilmu tidak datang begitu saja; ia mengalir melalui rantai keilmuan yang panjang, dari guru ke murid, dari murid ke generasi berikutnya; bersanad. Memutus rantai adab berarti memutus berkah ilmu itu sendiri.
Mungkin inilah yang tidak dipahami oleh Trans7 ketika mereka menyamakan penghormatan di pesantren dengan feodalisme. Feodalisme, dalam sejarahnya, lahir dari sistem kepemilikan tanah dan kekuasaan yang menindas. Hubungan antara tuan tanah dan rakyat jelata adalah hubungan ekonomi dan politik, penuh eksploitasi. Sedangkan hubungan kiai dan santri tidak diikat oleh uang, harta, atau jabatan, melainkan oleh ilmu dan bimbingan ruhani. Santri datang ke pesantren bukan karena diperintah, melainkan karena cinta kepada ilmu dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Dalam budaya Jawa, yang menjadi tanah kelahiran banyak pesantren di Nusantara, penghormatan kepada guru dan leluhur merupakan nilai luhur yang menata kehidupan sosial. Orang Jawa menyebutnya ngajeni, menempatkan seseorang sesuai dengan martabatnya. Kiai dihormati bukan karena kekuasaan, melainkan karena kedalaman ilmunya. Leluhur dihormati bukan karena darahnya, melainkan karena jasa dan kebijaksanaannya. Dalam kosmologi Jawa, keseimbangan hidup dijaga dengan sikap hormat, karena hormat menciptakan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Maka, ketika seorang santri mencium tangan kiai, itu bukan bentuk perbudakan, melainkan laku simbolik: bentuk kerendahan hati di hadapan sumber pengetahuan.
Namun di zaman yang mengagungkan kebebasan individual tanpa batas, adab sering kali disalahpahami sebagai pengekangan. Dalam pandangan modernisme yang dangkal, setiap hierarki harus dicurigai sebagai penindasan. Padahal, Islam dan kebudayaan Jawa memahami hierarki bukan sebagai kekuasaan, melainkan sebagai tatanan moral. Di dunia yang semakin gaduh ini, mungkin yang paling dibutuhkan manusia bukan lagi kebebasan tanpa arah, melainkan kemampuan untuk menundukkan ego dan menghormati sumber kebijaksanaan.
Ibn Khaldun dalam al-Muqaddimah menulis, feodalisme lahir ketika kekuasaan kehilangan moralitasnya dan berubah menjadi alat dominasi. Ia menyebutnya ‘asabiyyah, ikatan sosial yang membusuk oleh kepentingan dan nafsu. Feodalisme adalah penyakit kekuasaan yang tumbuh ketika manusia menyembah manusia. Tetapi dalam dunia pesantren, kiai tidak disembah. Ia dihormati karena menjadi jalan bagi ilmu, bagi pengetahuan, bukan tujuan dari penghormatan itu sendiri. Bahkan, para kiai besar seperti KH. Hasyim Asy‘ari dalam Adab al-‘Alim wa al-Muta‘allim menegaskan bahwa seorang guru tidak boleh merasa lebih tinggi dari muridnya, sebab ilmu adalah amanah, bukan alat untuk menguasai.
Dalam pandangan filsafat Islam, hubungan guru dan murid bersifat eksistensial. Mulla Sadra, seorang filsuf Persia abad ke-17, menulis dalam al-Asfar al-Arba‘ah bahwa pengetahuan sejati adalah perjalanan ruhani dari bentuk potensial menuju aktual. Guru berperan sebagai “pemandu ontologis” mengarahkan jiwa murid agar sampai pada wujud yang lebih sempurna. Dalam kerangka ini, menghormati guru berarti menghormati jalan menuju kesempurnaan diri. Begitu pula dengan gagasan Ibn ‘Arabi tentang adab al-haqq; adab terhadap Kebenaran. Manusia yang beradab kepada Tuhan akan menunjukkan adab yang sama kepada ciptaan-Nya, terutama kepada mereka yang menjadi perantara ilmu.
Sayangnya, logika spiritual seperti ini tidak mudah dipahami oleh media modern yang bekerja dengan logika sensasi. Tayangan Trans7 lebih sibuk mencari visual yang memancing emosi: santri mencium tangan, berjalan jongkok, menunduk atau menyebut nama gurunya dengan penuh rasa takut. Semua itu ditafsirkan secara dangkal sebagai simbol ketundukan tanpa daya. Padahal, di balik semua itu, ada cinta, ada keikhlasan, dan ada kesadaran bahwa ilmu bukan hasil dari debat logika semata, tapi juga hasil dari kesucian hati.
Feodalisme sejati bukanlah santri yang mencium tangan kiai, melainkan pejabat yang mencium tangan penguasa demi proyek. Feodalisme, bukan santri yang tunduk karena adab, tetapi mereka yang tunduk karena uang. Pesantren justru berdiri sebagai ruang moral terakhir di tengah dunia yang kehilangan nilai. Ketika birokrasi, politik, dan korporasi dikuasai oleh logika untung-rugi, pesantren mengajarkan keikhlasan dan kesederhanaan.
Mereka yang menyebut pesantren feodal lupa bahwa banyak kiai hidup sederhana. Mereka mengajar tanpa gaji, memberi makan santri dari hasil sawah, bahkan sering kali tidak menerima bayaran apa pun. Di mana letak feodalisme itu? Dalam sejarah Islam, para ulama justru menjadi kekuatan moral yang melawan tirani. Dari Imam Ahmad bin Hanbal yang menolak tunduk kepada khalifah, hingga KH. Hasyim Asy‘ari yang menggerakkan resolusi jihad melawan penjajah. Jika feodalisme berarti menindas, maka para kiai adalah anti-feodalisme sejati.
Dalam pandangan filsafat Islam, kebebasan sejati bukanlah kebebasan dari penghormatan, melainkan kebebasan dari hawa nafsu. Seorang murid yang menghormati guru sedang membebaskan dirinya dari kesombongan. Ia belajar untuk menundukkan ego agar ilmu bisa masuk dan tidak merusak. Seperti yang dikatakan Jalaluddin Rumi, “Tidak akan masuk air ke dalam cangkir yang penuh.” Adab adalah cara untuk mengosongkan diri agar pengetahuan bisa mengalir.
Kita hidup di zaman ketika kesantunan dianggap kemunduran, dan kritik tanpa adab disebut keberanian. Trans7, dalam tayangan itu, mencoba menjadi corong keberanian intelektual, tapi gagal membaca kedalaman budaya Islam dan Jawa yang melandasi kehidupan pesantren. Mereka melihat dengan kamera, tapi tidak dengan hati. Mereka merekam gerak tubuh, tapi gagal menangkap getaran jiwa.
Di pesantren, penghormatan bukanlah ritual kosong. Ia adalah jalan pembentukan karakter. Santri yang hormat kepada gurunya tidak akan berkhianat kepada ilmunya. Santri yang belajar adab sejak dini akan tumbuh menjadi manusia yang menjaga lisan dan tangannya. Ketika masyarakat hari ini sibuk mencari teladan moral di layar kaca, pesantren justru memproduksi manusia-manusia yang diam tapi bekerja, rendah hati tapi teguh memegang prinsip.
Sebagian besar masyarakat mungkin tidak tahu, bahwa di balik setiap santri yang mencium tangan kiai, ada doa yang tulus: agar ilmu mereka bermanfaat, agar langkah mereka diberkahi, agar dunia ini tetap memiliki secuil cahaya moral. Dan di balik tangan kiai yang dicium itu, ada keikhlasan untuk mengajar tanpa pamrih, untuk menjaga warisan spiritual yang kian tergerus zaman.
Trans7 boleh menuduh, boleh menafsir, boleh mengira bahwa pesantren adalah sisa feodalisme yang tersisa. Tapi kenyataannya, pesantrenlah yang menjaga agar bangsa ini tidak kehilangan rasa hormat. Adab yang mereka ajarkan adalah benteng terakhir peradaban di tengah dunia yang semakin bising oleh kebebasan tanpa tanggung jawab.
Feodalisme adalah ketika manusia menyembah kekuasaan, sementara adab adalah ketika manusia tunduk pada kebenaran. Kiai tidak memerintah dengan jabatan, tapi membimbing dengan kasih. Santri tidak melawan dengan kebencian, tapi mengabdi dengan cinta. Dalam dunia yang kehilangan kedalaman makna, mungkin hanya di pesantren kita masih bisa melihat manusia belajar menjadi manusia dengan rendah hati.
Dan mungkin, di situlah letak kesalahan terbesar Trans7: mereka gagal memahami bahwa dalam dunia pesantren, tunduk bukan berarti kalah, menghormati bukan berarti tak bebas, dan mencium tangan bukan tanda feodal, melainkan tanda cinta kepada ilmu, cinta kepada cahaya Tuhan yang bersemayam dalam laku manusia yang beradab.