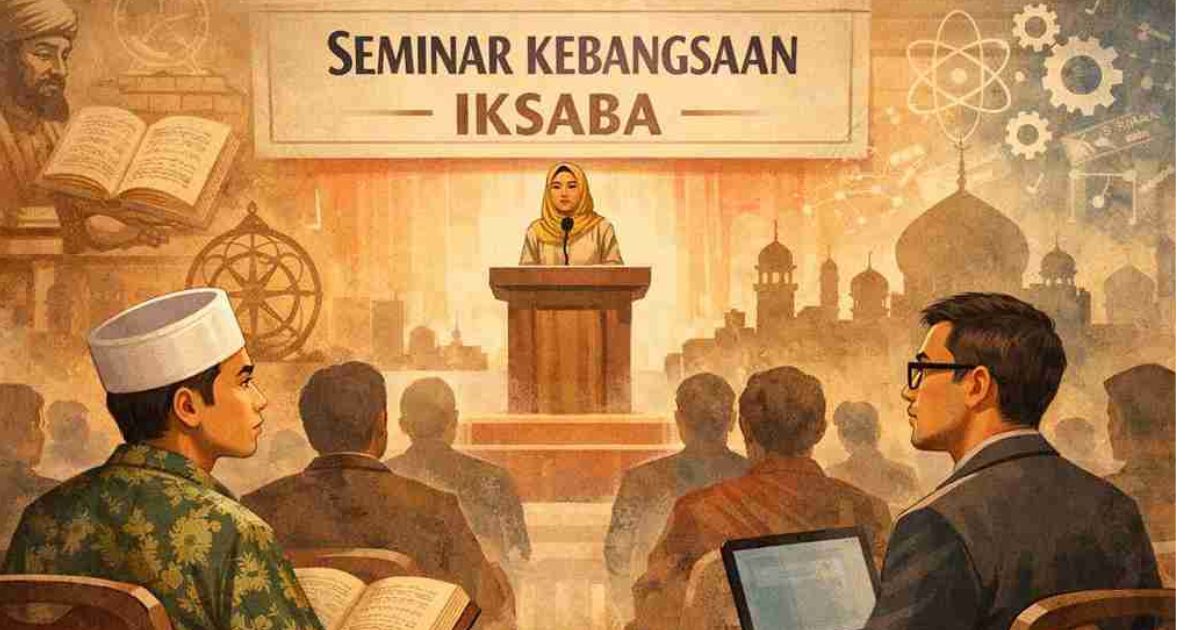Ada cerita menarik di tengah-tengah seminar kebangsaan yang telah menghadirkan para Alumni “Banyu Putih” dari berbagai daerah itu. Saat sesi dialog, terdapat pertanyaan menarik yang disampaikan kepada pemateri kedua, “Neng Yenny Wahid”. Pertanyaan dari salah satu alumni ini membuat forum pecah, yang awalnya berjalan secara serius.
Pertanyaannya: “Siapakah sebenarnya penemu kamus bahasa Madura?” tanyanya seloroh.
Pertanyaan ini disambut tepuk tangan dan tawa dari para hadirin yang hadir. Tetapi apabila dipahami secara serius, atensi dari penanya atas materi Neng Yenny yang sebelumnya sudah dipaparkan berarti benar-benar disimak dengan baik. Pertanyaan tersebut, kalau boleh penulis sedikit menanggapi, merupakan tanggapan atas materi Neng Yenny terkait koneksi keilmuan sains, teknologi, matematika, dan ilmu lain yang ada saat ini dengan para intelektual Muslim pada masa lalu.
Sederhananya begini, penanya semacam berimajinasi di tengah-tengah materi yang dipaparkan : “Jangan-jangan bahasa Madura juga memiliki koneksi keilmuan dengan intelektual terdahulu?”
Imajinasi dari penanya menjadi semacam titik penting sebagai bagian dari kegelisahan budaya. Fakta di lingkungan kita, bahasa daerah sedikit sekali yang mau meneliti. Misalnya meneliti sisi antropologis atau sisi linguistik, mengapa antara Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep terdapat kosakata yang berbeda. Belum lagi meneliti lebih jauh penyebaran dan akar mengapa terdapat pula bahasa madura sempalan yang disebut bahasa “Madura Swasta”.
Berangkat dari analisis inilah, Seminar Akademik Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Iksaba ini berarti berhasil memantik sebuah wacana baru dan berpikir kritis. Seminar kebangsaan ini sukses membuka cakrawala agar para alumni berimajinasi. Sebab pada dasarnya, kesuksesan yang dilahirkan oleh intelektual Muslim pada masa lalu berawal dari imajinasi-imajinasi atas kejadian yang terjadi di alam semesta dan keberanian untuk berpikir dalam menciptakan kemanfaatan.
Intelektual Santri dan Muslim
Seperti yang menjadi pembahasan dan yang disampaikan “Neng Yenny” bahwa santri jangan cuma belajar ilmu agama, melainkan juga belajar ilmu STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics). Pertanyaannya adalah: apakah hanya santri yang wajib menjembatani kesenjangan keilmuan dalam tradisi Islam selama ini yang telah lama tidur nyenyak?
Lebih jauh, Muslim memiliki makna yang luas, yaitu orang Islam. Santri adalah bagian dari kelompok Muslim tersebut, bukan satu-satunya. Dalam pengertian definitif ini berarti semua orang Islam memiliki tanggung jawab untuk berlomba-lomba mencapai cita-cita tersebut. Sebab itu, mahasiswa Muslim di universitas-universitas STEAM seperti Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan kampus lain yang sejenis juga memiliki tanggung jawab yang sama.
Oleh karenanya, dari sudut inilah sepertinya “angle” yang lebih penting untuk disorot daripada sekadar pengkultusan klasifikasi: santri dan non-santri. Keduanya tidak bisa dipisahkan apalagi dijadikan kambing hitam antara satu dengan yang lain. Sebuah pola pandang primitif tidak lagi perlu dipelihara dalam tradisi antar umat Muslim.
Seperti anggapan, “menjadi mahasiswa yang dicari hanya dunia, sementara akhirat dan akidahnya dilupakan”, atau anggapan, “menjadi santri tidak akan menjadi apa-apa dan hanya menjadi beban peradaban”.
Pengkultusan ini mempersempit gerak kolaboratif antar sesama umat Muslim. Apabila mau mencari contoh dengan menarik ke belakang, para intelektual Muslim yang memiliki kontribusi terhadap bidang keilmuan STEAM pada masa dahulu, biasanya disertai memiliki pengetahuan luas dalam agama, dan hafal Al-Qur’an seperti Ibnu Sina bahkan tidak terhitung jumlahnya memang ada dan tercatat dalam sejarah.
Kendati demikian. Lantas, apakah di zaman ini masih bisa ditemukan individu Muslim yang memiliki keluasan ilmu seperti masa dahulu tersebut? Bukan bermaksud meremehkan, tetapi pengelompokan ilmu pengetahuan di kampus Islam maupun kampus STEAM di berbagai institusi pendidikan dalam prodi-prodi tertentu, memberikan informasi bahwa keahlian satu bidang menjadi hal yang penting dan berdasar.
Status Muslim sebagai Bekal Kolaborasi
Karenanya, status Muslim adalah kekuatan yang tidak bisa dipisahkan apabila Islam ingin kembali seperti masa emasnya. Dalam pidato “Neng Yenny” ini, bukan saja dipahami bahwa hanya santri yang wajib belajar ilmu formal secara sekaligus dengan ilmu agama yang menjadi konsentrasi utamanya, tetapi secara bersamaan juga memotivasi mahasiswa STEAM yang notabenenya belajar keilmuan non agama agar bangga dengan status Muslim dalam dirinya saat mencapai prestasi yang telah diraih.
Dalam poin ini, pesantren tidak lagi terlihat sebagai lembaga yang serba salah. Sebuah mindset seolah-olah pesantren menjadi penyebab kemunduran islam karena hanya melahirkan agamawan, sementara perguruan tinggi STEAM yang mempelajari ilmu non agama diberdayakan karena dipandang sebagai modal utama dan dibutuhkan dalam bersaing di kancah industri dunia. Dari sini timbul pertanyaannya baru: apakah kampus-kampus itu hari ini memang benar telah melahirkan mahasiswa muslim yang berdaya global seperti yang dipahami tersebut? Paling jauh biasanya hanya menjadi pejabat perusahaan asing di luar negeri bukan pemilik perusahaan.
Mindset ini merupakan persoalan utama yang membuat pesantren kerap memaksa melakukan hal yang bukan menjadi tanggung jawab utamanya: memaksa bersaing dengan perguruan tinggi STEAM, hingga akhirnya nilai-nilai pesantren tercerabut dan terlihat seperti lembaga konvensional pada umumnya. Walaupun pada akhirnya lahir formula baru pendidikan pesantren yang disebut “Pesantren Modern”, hal ini merupakan keautentikan yang menjadi pembahasan berbeda dan tersendiri.
Pun kalangan pesantren pragmatis sering memandang kajian keilmuan STEAM sebagai kelas kedua dengan alasan karena “hanya” ilmu dunia saja. Misalnya alasan itu berangkat dari sebuah konsep bahwa ilmu-ilmu tersebut bukan ilmu fardu ‘ain. Jika itu terjadi berarti merupakan kesalahan penempatan konsep terhadap objek yang berkembang. Konsep tersebut pada dasarnya dipahami untuk diamalkan dan memahami dosis ilmu yang perlu dicapai dalam perspektif agama—bukan lantas menilai keniscayaan yang terjadi.
Akhirnya, penting gaya bahasa dari pernyataan yang dipakai Surah Al-Kafirun dalam usahanya membangun nilai kolaborasi umat Muslim dan non-Muslim. Jika dikaitkan dengan konteks ini, yang perlu disampaikan oleh masing-masing dari dua aliran ilmu terhadap satu sama lain adalah: “Tugasku adalah tugasku, dan tugasmu adalah tugasmu.” Walhasil artinya selagi Muslim, mari bergandengan tangan menciptakan peradaban keilmuan yang baru.
Apabila santri tidak paham mekanika kuantum, itu hal yang wajar karena kitab fikih tidak mempelajari hal tersebut. Demikian pula ketika orang STEAM tidak paham kaidah-kaidah ushul fikih, mubtada’, khabar, atau ibadahnya, fatihahnya, sujudnya, tidak sebagus santri, itu juga hal yang wajar. Santri adalah penjaga keaslian agama, sementara peneliti STEAM bersaing membawa status agamanya di kancah dunia. Masak kalah dengan Muhammad Salah dalam bidang atlet, atau Selebrasi Sujud Coach Indra Sjafri? Ini refleksi bagi umat Muslim semuanya. Dan tanggung jawab umat Muslim seluruhnya.
Wallāhu a‘lamu bi nafs al-amr.